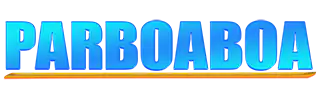PARBOABOA, Jakarta - PT Toba Pulp Lestari (TPL) diduga melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat. Kali ini, korbannya adalah Masyarakat Adat Natinggir di Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (7/8/2025) pagi, ketika ratusan karyawan dan petugas keamanan PT TPL menanam eukaliptus di lahan pertanian milik warga.
Upaya warga untuk menghentikan aktivitas itu justru berujung pada tindak kekerasan, hingga menyebabkan satu orang mengalami luka di bagian leher.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mengecam keras tindakan tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif KSPPM, Roki Pasaribu, aksi penggusuran ini bukan hanya bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya, tetapi juga disertai kekerasan yang semakin brutal dan di luar kendali.
Ia menambahkan, PT TPL juga melakukan perusakan rumah-rumah warga, bahkan melempari bangunan saat anak-anak masih berada di dalamnya. Bahkan, empat staf KSPPM yang mendampingi warga di lokasi juga menjadi korban kekerasan.
Tindakan ini, menurutnya, memperpanjang daftar dugaan pelanggaran PT TPL terhadap konstitusi agraria dan memperburuk krisis agraria di Sumatera Utara.
Selama lebih dari empat dekade, PT TPL menguasai 291.263 hektare lahan di provinsi tersebut untuk hutan tanaman industri, termasuk 33.422,37 hektare wilayah adat dari 23 komunitas di 12 kabupaten.
Data KSPPM menunjukkan, setidaknya 470 masyarakat adat telah menjadi korban selama konflik berlangsung di mana dua orang meninggal dunia, 208 mengalami kekerasan fisik, dan 260 dikriminalisasi.
Selain itu, ada dugaan praktik perbudakan modern terhadap pekerja perusahaan.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa operasi PT TPL sarat pelanggaran hukum.
Ia menguraikan bahwa area konsesi perusahaan mencakup 188.055 hektare, di antaranya 28 persen (sekitar 52.668,66 hektare) berada di kawasan yang secara hukum tidak diperbolehkan, seperti Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, dan Areal Penggunaan Lain.
Lebih ironis lagi, klaim kawasan hutan di Sumatera Utara selama ini baru sebatas “penunjukan” tanpa proses “penetapan” yang melibatkan persetujuan masyarakat adat yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut.
Menurut Dewi, hal ini menunjukkan adanya cacat hukum, maladministrasi, manipulasi prosedur, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin konsesi.
Dengan demikian, keberadaan PT TPL beserta operasinya merupakan praktik ilegal yang difasilitasi negara.
Ia juga menyoroti bahwa Sumatera Utara menjadi salah satu titik panas konflik agraria di Indonesia, terutama akibat klaim Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh korporasi besar.
Dalam satu dekade terakhir, provinsi ini menempati peringkat pertama konflik agraria, dengan 275 kasus mencakup 655.285,69 hektare lahan, berdampak pada lebih dari 227 ribu rumah tangga.
KPA dan KSPPM mendesak PT TPL segera menghentikan operasi ilegal serta segala bentuk penggusuran dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat Natinggir, khususnya perempuan dan anak-anak.
Mereka juga meminta Kapolres Toba mengusut tuntas pelanggaran hukum tersebut, dan Kementerian Kehutanan mencabut izin HTI PT TPL.
Selain itu, kedua lembaga tersebut menuntut Kementerian Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN untuk melepaskan klaim negara atas tanah adat sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan pemulihan hak masyarakat adat se-Tano Batak.
Mereka juga meminta Presiden RI untuk melaksanakan reforma agraria, menyelesaikan konflik, dan menghentikan monopoli tanah akibat klaim sepihak atas kawasan hutan negara yang merampas wilayah adat.