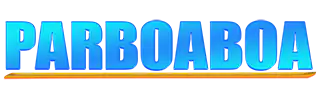Tulisan-1
PARBOABOA, Pematangsiantar – “Kau rezekiku, aku mau cari rezeki. Tolong kerja sama denganku agar keluargaku bisa hidup.” Pak Tiara berucap untuk merayu pohon aren.
Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, lelaki berusia 46 tahun itu memiliki ritus yang diwariskan turun-temurun: mangelek. Artinya, membujuk pohon aren dengan kalimat sederhana namun penuh harap.
Rutinitas hariannya dimulai dengan marragat—menyadap nira dari pohon aren—yang dilakukan dua kali sehari, pagi dan sore. Proses ini melibatkan penyayatan halus pada bagian tandan bunga jantan (mayang) agar air nira dapat mengalir dan ditampung di dalam wadah bambu atau plastik.
Penyadapan tidak bisa tergesa-gesa; butuh ketelatenan dan rasa. Jika terlalu dalam menyayat dapat merusak pohon, sementara bila dangkal hasil yang keluar tak maksimal. Yang dipotong dari pohon adalah tangkainya atau disebut tangki bunga jantan. Itulah yang dideres.
Bagi seorang paragat, pohon aren bukan sekadar objek produksi melainkan makhluk hidup yang memiliki jiwa. Ada ikatan emosional yang terbangun dari kebiasaan harian, seolah terjalin hubungan batin antara penyadap dan pohon yang dirawatnya.
“Rasanya seperti terkoneksi. Seperti seorang laki-laki yang sedang merayu perempuan,” tuturnya.
Perumpamaan itu tak berlebihan. Setiap hari dia mendekati pohon dengan kelembutan dan kesabaran—memilih waktu yang tepat, menyentuh dengan hati-hati, dan menyayat dengan perasaan.
Tak bisa dipaksa, karena jika terlalu tergesa pohon dapat ‘tersinggung’ sehingga ogah mengeluarkan air. Dalam hubungan itu ada rasa saling percaya yang tumbuh pelan-pelan hingga pohon memberikan hasil terbaiknya.
Sebelum memanjat pohon dan memulai penyadapan, Pak Tiara senantiasa menyempatkan diri untuk berdoa. Terlebih ketika pertama kali sebuah pohon mulai disadap. Ada sebuah tradisi yang disebut tuak pamuang—yakni mengadakan makan bersama seperti memotong ayam di lapo [lepau] sebagai bentuk syukur dan permohonan agar pohon tersebut subur dan menghasilkan tuak dengan lancar.

Membangun Rumah
Dalam satu hari Pak Tiara bisa memanen hingga tiga kaleng tuak. Satu kaleng berisi 10 teko, dan setiap teko dijual Rp11.000. Artinya, dalam sehari ia bisa berpenghasilan sekitar Rp330.000. Jumlah yang cukup stabil dan layak, terutama di daerah seperti Sionggang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Ia mulai berjualan sekitar pukul lima sore dan tutup antara pukul sebelas malam hingga dini hari meskipun ada pula pelanggan yang betah minum hingga subuh. Di laponya sendiri ia mematok harga Rp3.500 per cangkir.
Tak hanya untuk konsumsi lapo di sekitar kampung, tuaknya. Dia juga memiliki beberapa agen tetap yang datang mengambil minuman beralkohol itu untuk dijual kembali ke berbagai tempat lain.
Setiap sore, para reseller akan datang menjemput hasil sadapan. Jaringan distribusi ini membuat tuaknya dikenal luas. Tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar Sionggang, tetapi juga sampai ke Panei Tongah dan Bah Jambi.
Hal ini secara tidak langsung membantu memperkenalkan kualitas tuak dari Sionggang ke lebih banyak orang. Ia pun merasa bangga karena hasil kerjanya bisa turut menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus menopang kehidupan banyak orang lainnya.
Bagi para paragat seperti Tiara yang tidak memiliki lahan atau pohon aren sendiri, sistem kerja yang umum digunakan adalah bagi hasil. Setiap minggu, hasil penjualan tuak dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik pohon dan Tiara.
Sistem ini memungkinkan kerja sama yang saling menguntungkan: paragat bisa terus menjalankan aktivitas produksinya tanpa harus memiliki aset tanah, sementara pemilik pohon tetap mendapatkan pemasukan dari pohon miliknya. Pola kerja seperti ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari ekonomi lokal yang berbasis pada kepercayaan dan relasi sosial di tingkat komunitas.
Lalu, apakah pekerjaan sebagai paragat menjanjikan secara ekonomi? Dengan mantap ia menjawab, “Benar, penghasilanku dari tuak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”
Penghasilan ini memberinya kestabilan ekonomi tanpa harus merantau jauh dari kampung halaman.
“Dari tuak ini, aku bisa bangun rumah dan sekolahkan anak-anak,” ungkapnya dengan bangga.
Kalimat sederhana itu merangkum perjalanan panjang seorang pekerja lokal yang menggantungkan harapannya pada pohon-pohon aren yang setia memberi rezeki.

Hasil kerja sebagai paragat selama bertahun-tahun telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan Pak Tiara dan keluarganya. Dari penghasilan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit ia berhasil membangun rumah sendiri—sebuah pencapaian yang lahir dari ketekunan dan kesabaran dalam menjalani profesi tradisional ini.
Tak hanya itu, pekerjaan sebagai penyadap tuak juga memberinya kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Baginya, menyekolahkan anak adalah bentuk investasi masa depan dan bukti bahwa maragat, meski sering dipandang sebelah mata, tetap memiliki daya hidup yang kuat jika dikelola dengan tekun.
Selain itu, dengan tetap tinggal di tanah kelahiran ia bisa menjalani hidup sederhana namun layak sambil terus melestarikan tradisi turun-temurun sebagai penderes tuak.
Ketika ditanya soal tips atau trik agar produksi tuaknya banyak dan lancar, ia menjawab dengan rendah hati, “Aku cuma bisa membujuk Tuhan.”
Ungkapan ini bukan sekadar candaan tapi menunjukkan keyakinannya bahwa hasil terbaik berasal dari restu Yang Maha Kuasa.

Keahlian Khusus
Pria kelahiran 1982 ini telah 26 tahun menekuni pekerjaannya sebagai paragat atau penderes tuak dan hingga kini tetap setia menggantungkan hidup dari air nira yang diturunkan langsung dari pucuk-pucuk pohon aren untuk menghidupi keluarga.
Bagi sebagian orang, menjadi paragat mungkin pilihan karena keterpaksaan. Namun bagi pria ini, jalan hidup sebagai penyadap tuak adalah warisan yang sudah tertanam sejak ia dilahirkan.
“Orang tuaku dulu juga paragat,” katanya. “Jadi bisa dibilang, ilmuku soal tuak itu sudah dari lahir.”
Meski telah akrab dengan dunia tuak sejak kecil, ia baru benar-benar menekuni pekerjaan ini secara penuh waktu pada usia 26 tahun. Keputusan itu bukan semata mengikuti jejak orang tua melainkan juga karena keterampilan yang dimilikinya memang mengarah ke sana.
“Nggak semua orang yang punya tanah dan pohon tuak bisa langsung maragat,” jelasnya. “Ini bukan cuma soal keberanian naik pohon, tapi ada teknik dan rasa yang harus dilatih.”
Menyadap tuak memang membutuhkan keahlian khusus—dari mengenali kapan waktu terbaik untuk meragat, bagaimana menyayat mayang agar tak rusak, hingga menjaga kebersihan dan keaslian nira.
“Kualitas tuak itu juga sangat tergantung pada paragatnya,” ujar Pak Tiara.
Teknik menyayat, waktu penyadapan, hingga cara merawat alat dan wadah penyimpanan, semuanya memengaruhi hasil akhir.
Ada tips penting dalam menjaga kualitas dan masa ketahanan tuak yaitu dengan memperhatikan kebersihan wadah penyimpanan. Jerigen atau tempat penampung nira harus dalam kondisi benar-benar bersih agar tuak tidak cepat mengalami fermentasi berlebihan yang menyebabkan rasa menjadi terlalu asam atau bahkan basi.
“Kuncinya di kebersihan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa kelalaian sekecil apa saja dalam hal sanitasi dapat memengaruhi cita rasa tuak secara drastis. Oleh karena itu, setiap paragat atau pelaku usaha tuak disarankan untuk selalu mencuci dan mengeringkan wadah sebelum digunakan, serta tidak mencampur tuak baru dengan sisa lama yang sudah mulai asam.
Dengan perawatan yang tepat kualitas tuak bisa terjaga lebih lama dan tetap layak dikonsumsi dalam kondisi segar.

Menariknya lagi, meskipun dua paragat menyadap dari pohon-pohon yang tumbuh di lahan yang sama, tuak yang mereka peroleh belum tentu memiliki kualitas yang serupa. Perbedaan itu bukan karena kondisi tanah atau pohonnya semata melainkan karena tangan yang mengolahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa menjadi maragat bukan sekadar soal memanjat dan menyadap melainkan seni yang menggabungkan pengalaman, ketelatenan, dan rasa tanggung jawab terhadap kualitas. Tuak yang baik tidak hanya dihasilkan dari pohon yang sehat tetapi juga oleh tangan yang piawai dan hati yang tulus dalam bekerja.
Ia pun mengakui dengan jujur, “Aku juga memutuskan jadi paragat karena enggak punya skill lain, he..he..he…” candanya, diselingi tawa ringan yang menandakan penerimaan sepenuhnya terhadap pekerjaan yang kini menjadi tumpuan hidup.
Ia memandang pohon aren bukan sekadar sumber nira, melainkan ladang rezeki yang harus dijaga dan dihormati.
Gaya Hidup
Ajis, 34 tahun, merupakan salah satu pelanggan setia yang mengenal tuak sejak usia 21. Baginya, tuak bukan sekadar minuman tapi bagian dari gaya hidup yang terhubung dengan akar budaya Batak. “Tuak ini alami, beda dengan alkohol pabrikan,” katanya.
Ia melihat lapo tuak sebagai ruang sosial yang inklusif—tempat segala hal bisa diperbincangkan, mulai dari urusan bisnis, politik lokal, hingga persoalan pendidikan.
Fungsi lapo melampaui sekadar tempat berkumpul; ia menjadi forum publik informal yang mempertahankan nilai-nilai keterbukaan, gotong royong, dan relasi antargenerasi.
Menurut Ajis, keaslian lapo tradisional dengan bangunan sederhana masih sulit tergantikan. “Tak salah mengikuti zaman, tapi suasana lapo yang kayak begini lebih tenang dan akrab dibanding yang sudah mirip kafe dengan karaoke.”
Baginya, lapo bukan soal fasilitas, tetapi soal rasa dan ikatan—pengalaman sosial yang tulus, dan jauh dari hiruk-pikuk hiburan artifisial.
Perubahan gaya lapo dengan fasilitas modern seperti karaoke memang menunjukkan adanya dinamika konsumsi. Namun, pelanggan seperti Ajis tetap mencari pengalaman yang lebih otentik—tempat di mana obrolan mengalir tanpa polesan, dan tuak dinikmati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang penuh makna. (Bersambung)
Penulis: Novriani Tambunan, Indah Cahyani, Alberto Nainggolan
Editor : P. Hasudungan Sirait
Catatan: tulisan ini merupakan karya kelompok peserta Sekolah Jurnalisme Parboaboa (SJP) Pematangsiantar, Batch 2. SJP merupakan buah kerja sama Parboaboa.com dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.